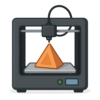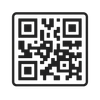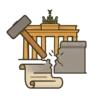Tembok yang Runtuh, Dunia yang Menyatu
Namaku Anja, dan pada musim gugur tahun 1989, aku adalah seorang remaja yang tinggal di Berlin Timur. Bagiku dan semua orang yang kukenal, Tembok Berlin adalah bagian dari kehidupan kami. Tembok itu bukan sekadar dinding beton dan kawat berduri. Tembok itu adalah monster abu-abu yang membelah kota kami, memisahkan jalanan, memisahkan teman, dan bahkan memisahkan keluarga. Bibi dan sepupuku tinggal di Berlin Barat, begitu dekat hingga aku bisa melihat lampu-lampu apartemen mereka dari jendelaku, namun terasa seperti di planet lain. Kehidupan di Timur terasa terkendali dan sunyi. Bangunan-bangunan tampak muram, dan orang-orang sering berbicara dengan berbisik, seolah-olah dinding pun punya telinga. Namun, di dalam rumah kami yang kecil, ada kehangatan. Ayah, Ibu, kakakku Klaus, dan aku memiliki ikatan yang kuat, dipenuhi dengan tawa dan cerita di sekitar meja makan. Kami menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Namun, pada tahun itu, sesuatu yang berbeda terasa di udara. Bisikan-bisikan perubahan menyebar ke seluruh Eropa Timur. Kami mendengar tentang protes damai di kota-kota lain seperti Leipzig, di mana orang-orang berbaris menuntut kebebasan. Kami mendengar bahwa Hongaria telah membuka perbatasannya dengan Austria. Harapan adalah hal yang berbahaya, tetapi juga indah. Setiap malam, orang tuaku akan mendengarkan radio dengan saksama, wajah mereka tegang. Bisakah sebuah tembok yang telah berdiri selama 28 tahun benar-benar runtuh? Kami tidak berani memikirkannya, tetapi di lubuk hati kami yang terdalam, sebuah pertanyaan kecil mulai tumbuh: bagaimana jika?
Pada malam tanggal 9 November 1989, udara terasa dingin dan menusuk, seperti malam-malam lainnya di bulan November. Keluargaku berkumpul di sekitar televisi kecil kami, menonton konferensi pers pemerintah yang membosankan. Tiba-tiba, seorang pejabat bernama Günter Schabowski mulai berbicara tentang peraturan perjalanan baru. Dia tampak sedikit bingung, membaca dari selembar kertas. Seorang wartawan bertanya kapan peraturan itu akan berlaku. Schabowski mengangkat bahu dan berkata, "Sejauh yang saya tahu... segera, tanpa penundaan." Hening. Kami saling berpandangan di ruang tamu kami yang remang-remang. Apakah kami salah dengar? Ayahku mematikan suara televisi. Apakah ini lelucon? Sebuah jebakan? Ketidakpercayaan menyelimuti kami. Kemudian, telepon berdering. Tetangga kami menelepon, suaranya bergetar karena kegembiraan dan kebingungan. Mereka juga mendengarnya. Segera, seluruh gedung apartemen kami ramai dengan suara pintu terbuka dan orang-orang berbicara dengan penuh semangat di lorong. Sebuah energi yang belum pernah kurasakan sebelumnya mulai berdenyut di seluruh kota. "Kita harus pergi dan melihat," kata Ayahku, suaranya mantap meskipun matanya menunjukkan keraguan. "Mereka tidak bisa menghentikan kita semua." Kami mengenakan mantel terhangat kami dan melangkah keluar ke jalanan yang gelap. Jalanan itu tidak lagi sepi. Ratusan, lalu ribuan orang berjalan ke arah yang sama, menuju pos pemeriksaan Bornholmer Straße. Rasanya seperti sungai manusia yang mengalir menuju harapan. Kerumunan di pos pemeriksaan itu sangat besar. Ada begitu banyak orang, semuanya berdesakan, wajah mereka diterangi oleh lampu sorot yang keras. Para penjaga perbatasan tampak sama bingungnya dengan kami. Mereka berdiri dengan senjata mereka, tetapi mereka kalah jumlah. Kami mulai bernyanyi, bukan dengan amarah, tetapi dengan permohonan yang kuat: "Buka gerbangnya! Buka gerbangnya!" Kami menunggu selama berjam-jam dalam ketegangan. Para penjaga terus-menerus menelepon, jelas tidak menerima perintah yang jelas. Akhirnya, sesaat sebelum tengah malam, seorang perwira memberi isyarat. Palang bergaris itu terangkat. Gerbang itu terbuka. Untuk sesaat, terjadi keheningan yang luar biasa, diikuti oleh ledakan sorak-sorai yang mengguncang langit. Orang-orang menangis, berpelukan, tertawa. Itu adalah suara kebebasan yang memekakkan telinga.
Menggenggam erat tangan Ayah dan Ibu, aku mengambil langkah pertamaku ke Berlin Barat. Rasanya seperti melangkah dari dunia hitam-putih ke dunia penuh warna. Udara terasa berbeda, lebih ringan. Mataku terbelalak melihat pemandangan itu. Lampu neon dari toko-toko berkelap-kelip dengan warna-warna cerah, mengiklankan merek-merek yang hanya pernah kudengar dalam bisikan. Jalanan begitu terang, berbeda dengan lingkungan kami yang remang-remang di Timur. Aroma yang belum pernah kuhirup sebelumnya memenuhi udara—sosis panggang yang gurih, kacang almond manis, dan bau parfum yang aneh. Musik yang berbeda, musik rock yang energik, mengalun dari pintu-pintu bar yang terbuka, mengundang kami masuk. Tapi yang paling luar biasa adalah sambutannya. Warga Berlin Barat berbaris di jalanan untuk menyambut kami. Mereka bertepuk tangan dan bersorak seolah-olah kami adalah pahlawan yang kembali dari perang. Orang asing memeluk kami, air mata mengalir di pipi mereka. Seorang wanita tua menekan sebuah pisang—buah yang sangat langka bagi kami—ke tangan Ibuku. Seseorang memberiku sebatang cokelat, rasanya begitu kaya dan lezat. Mereka berbagi kegembiraan kami, meneriakkan, "Selamat datang, saudara dan saudari!" Pada saat itu, aku menyadari bahwa Tembok itu tidak hanya membelah beton dan kawat. Tembok itu telah membelah hati, membelah sebuah bangsa. Malam itu, di bawah langit yang sama yang selalu kami bagi, kami menjadi satu lagi. Seluruh pengalaman itu terasa seperti mimpi, mimpi indah yang aku takut akan berakhir jika aku berkedip.
Pada hari-hari berikutnya, Tembok itu sendiri mulai lenyap. Orang-orang datang dari seluruh penjuru dengan palu dan pahat, memukul-mukul beton. Mereka disebut "Mauerspechte"—burung pelatuk tembok. Mereka mengubah simbol penindasan menjadi suvenir kebebasan, setiap kepingan beton menjadi pengingat akan kekuatan kami. Bagian-bagian Tembok yang masih berdiri menjadi kanvas raksasa. Seniman dan orang biasa melukis mural yang penuh warna, pesan-pesan harapan, perdamaian, dan persatuan. Tak lama kemudian, bibi dan sepupuku datang mengunjungi kami di apartemen kami. Tidak ada lagi lambaian tangan dari kejauhan. Kami bisa berpelukan erat. Keluargaku, dan negaraku, secara perlahan disatukan kembali. Malam itu mengajarkanku sebuah pelajaran yang tak akan pernah kulupakan. Sejarah tidak hanya dibuat oleh para pemimpin atau jenderal. Sejarah dibuat oleh orang-orang biasa sepertiku dan keluargaku, yang berani berharap akan sesuatu yang lebih baik. Sejarah dibuat oleh ribuan suara yang bersatu untuk menuntut perubahan. Tidak ada tembok, setinggi atau setebal apa pun, yang dapat selamanya menahan keinginan manusia untuk terhubung dan bebas. Keinginan itu akan selalu, pada akhirnya, menemukan jalan untuk menerobos.
Aktivitas
Ikuti Kuis
Uji apa yang telah kamu pelajari dengan kuis yang menyenangkan!
Berkreasilah dengan warna!
Cetak halaman buku mewarnai tentang topik ini.